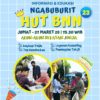Pada pertengahan 2012, penulis mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Balai Besar Rehabilitasi Lido milik instansi Badan Narkotika Nasional. Kunjungan itu tak terencana karena penulis mengenal salah seorang pegawai di balai rehabilitasi narkoba yang terbesar di Indonesia. Berkunjung ke area rehabilitasi merupakan kali pertama, kala itu belum banyak ilmu tentang seluk-beluk narkoba yang dipahami penulis.
Memasuki area umum pengunjung yang dipenuhi dengan para klien rehabilitasi menimbulkan ketidaknyamanan tersendiri. Ada perasaan ‘tidak aman’ yang dirasakan untuk pertama kalinya. Padahal para klien rehabilitasi pun biasa saja, mereka melakukan kegiatan rutin tanpa memedulikan penulis, si pengunjung dadakan.
Sepanjang jalan melewati pasien yang direhabilitasi, penulis menundukkan pandangan. Menjaga sebisa mungkin untuk tidak menatap mata mereka. Bukan, bukan karena takut. Tetapi penulis berusaha untuk tidak memandang mereka sambil melabeli stigma tertentu kepada para klien rehabilitasi. Tepatnya, penulis tidak ingin kecolongan memberikan stigma negatif melalui tatapan mata kepada mereka.
Saat itu penulis berpikir, ternyata sulit sekali menetralkan isi kepala supaya tidak memandang para penyalahguna narkoba dengan tatapan yang berbeda. Bagaimana jika muncul tatapan kasihan, takut, atau bahkan risih dengan keberadaan mereka? Jadi daripada bersikap salah, lebih baik menunduk, menghindarkan potensi untuk memandang mereka dengan stigma. Demi menjaga para klien rehabilitasi dari ketidaknyamanan yang berpotensi timbul akibat pemahaman yang masih minim dari orang lain.
Pengalaman tersebut memicu penulis untuk mempelajari lebih lanjut tentang stigma yang selama ini lekat dengan penyalahguna narkoba. Banyak anggapan yang beredar di masyarakat bahwa orang yang mengonsumsi zat adiksi sama saja dengan melakukan tindak kriminal karena pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Stigma yang diberikan ini tidak memedulikan latar belakang mengapa seseorang menyalahgunakan narkoba, satu hal yang disepakati bersama dalam masyarakat adalah bahwa perilaku penyalahgunaan tersebut membuat mereka dianggap berbeda dengan masyarakat biasa.
Apa itu Stigma?
Konsep dari stigma diformulasikan oleh Erving Goffman dalam buku berjudul ‘Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity’. Menurut Goffman (1), stigma merupakan atribut, perilaku, atau reputasi yang menempatkan seseorang ‘di luar norma sosial’. Hal ini berkonotasi negatif, mendiskreditkan individu maupun sekelompok orang dengan atribut negatif, membuat mereka dianggap lebih tidak berharga.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muncan et al. (2) disebutkan bahwa stigma terhadap penyalahgunaan narkoba dan diskriminasi yang ditimbulkan stigma tersebut, akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Terdapat dua jenis stigma yang disampaikan oleh Earnshaw dan Chaudoir (3), yaitu enacted stigma dan anticipated stigma.
Jika dikaitkan dengan narkoba, enacted stigma didefinisikan sebagai pengalaman dari diskriminasi maupun prasangka yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba oleh orang-orang yang mengonsumsi narkoba. Sementara anticipated stigma merupakan ekspektasi individu bahwa dirinya akan mendapat diskriminasi atau tuduhan di masa mendatang, sehingga penyalahguna narkoba menginternalisasi stigma tersebut ke dalam dirinya agar kelak bisa menerima pandangan negatif maupun merendahkan dari orang lain akibat mengonsumsi narkoba (3).
Penelitian oleh Muncan et al. dengan metode interview dilakukan kepada 32 orang pengguna narkoba jenis suntik di New York pada tahun 2020, dari keseluruhan responden terdapat 78,1% yang melaporkan pernah mengalami bentuk stigma ketika mengakses fasilitas kesehatan (2). Sebagian partisipan mengungkapkan bahwa mereka mengalami enacted stigma yang dilakukan oleh praktisi kesehatan yang menggunakan kalimat menyakitkan dan judgemental ketika mengetahui status mereka sebagai penyalahguna narkoba.
Stigma yang diberikan tidak hanya berupa komentar tendensius, acapkali orang bisa tiba-tiba berhenti mengajak bicara, mengabaikan, atau terang-terangan menjauh saat tahu status pemakaian narkoba. Bahkan jenis pemakaian zat adiksi pun juga mempengaruhi stigma yang diberikan kepada penggunanya, misal zat yang ilegal (misal narkoba) akan mendapatkan stigma lebih berat dibandingkan adiksi pada alkohol maupun rokok (4).
Dalam penelitian yang sama, 59,4% responden mengekspresikan ketakutan akan mendapatkan stigma dan diskriminasi, yang termasuk sebagai anticipated stigma, sehingga mereka memilih untuk menghindari fasilitas dan praktisi kesehatan meskipun sedang sakit (2). Stigma ini juga biasanya merupakan akumulasi kekhawatiran dari pengalaman sebelumnya ketika mendapatkan pandangan negatif dari orang lain. Hal tersebut menjadi penyebab terbentuknya prasangka negatif dan sikap pasif untuk mendapatkan pelayanan maupun perawatan di fasilitas umum.
Menurut Corrigan dan Kleinlein dalam penelitian Ardani dan Handayani (5), stigma memiliki dua sudut pandang untuk dipahami, yaitu stigma masyarakat dan stigma pada diri sendiri (self-stigma). Stigma masyarakat terbentuk ketika sekelompok orang setuju dengan stereotip negatif untuk seseorang, sementara self-stigma adalah penyalahguna narkoba menerapkan stigma untuk dirinya sendiri karena kondisinya.
Self-stigma ini dapat mempengaruhi sudut pandang penyalahguna narkoba pada dirinya sendiri, dia bisa menginternalisasi pandangan negatif orang lain untuk dirinya, sehingga lama kelamaan dia meyakini bahwa itu memang sifat aslinya. Memperburuk kepercayaan diri dan selalu merasa rendah diri.
Salah satu masalah yang muncul akibat stigma ini adalah ketakutan yang dialami oleh para penyalahguna, mereka takut akan mendapat perlakuan diskriminatif yang memberi dampak lebih panjang. Salah satunya adalah resistensi terhadap layanan rehabilitasi, meskipun mereka memiliki keinginan untuk pulih dan melakukan program rehabilitasi, rasa malu dan takut lebih mendominasi. Sehingga ada keengganan dari mereka untuk memulai mengakses layanan rehabilitasi.
Selain itu, mereka juga takut bahwa statusnya terungkap ketika mereka mengakses layanan kesehatan. Padahal mereka juga membutuhkan informasi dan pemahaman tentang proses rehabilitasi dan dampak penyerta bagi tubuh maupun psikis para penyalahguna. Self-stigma ini bisa menjadi bentuk internalisasi stigma yang akan berdampak buruk secara psikologis. Berbagai bentuk stigma, baik dari masyarakat maupun diri sendiri dapat mengarahkan individu untuk melabeli diri bahwa mereka tidak dapat diterima saat mengakses pengobatan (4).
Corrigan et al. menyampaikan bahwa dampak dari stigma antara lain adalah ‘why try effect’, misalnya orang yang sudah menginternalisasi stigma buruk dalam dirinya akan memiliki anggapan ‘mengapa saya harus mencoba berobat?’; ‘mengapa saya harus rehabilitasi?’; ‘mengapa saya harus bekerja?’ dan ‘mengapa saya harus mencoba suatu hal, padahal saya tidak berharga’ (4).
Selain itu diskriminasi terhadap penyalahguna narkoba dalam masyarakat juga dapat menurunkan potensi mereka untuk melakukan kegiatan secara normal, misal dalam bekerja. Padahal aktivitas bekerja selain membantu mereka mengalihkan aktivitas juga dapat mendukung program pemulihan dari penyalahgunaan narkoba. Jika akses terhadap mata pencaharian juga dibatasi, ini akan mengganggu kemampuan mereka untuk membayar layanan pengobatan maupun rehabilitasi. Lebih-lebih jika mereka harus menggunakan layanan publik, individu yang merasa terstigma akan mengurangi kemungkinan mencari bantuan, mengakhiri pengobatan, serta mengurangi kepercayaan diri untuk menolak adiksi narkoba (4).
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sendiri selama beberapa tahun terakhir makin gencar menggalakkan kampanye tentang layanan rehabilitasi yang dapat diakses oleh para penyalahguna narkoba secara gratis. Informasi identitas para klien rehabilitasi juga dijamin kerahasiaannya, namun hal tersebut belum banyak merubah stigma dari masyarakat umum tentang penyalahguna narkoba. Pesan tentang layanan rehabilitasi ini disuarakan melalui banyak platform, mulai dari media non-elektronik, media elektronik, maupun media sosial. Hanya saja, kampanye tentang gerakan anti stigma kepada para penyalahguna narkoba masih sangat minim.
Apalagi pandangan umum yang berlaku di masyarakat bahwa narkoba erat kaitannya dengan kriminalitas dan aspek hukum, membuat stigma bahwa penyalahguna narkoba berhak untuk pulih melalui rehabilitasi sulit dipahami. Dalam satu contoh, misal seorang penyalahguna narkoba bisa menjalani tahapan proses rehabilitasi hingga pulih, namun saat kembali berinteraksi dengan masyarakat masih harus menerima stigma negatif terkait statusnya sebagai mantan penyalahguna. Akibatnya, potensi untuk terjadinya relapse (kembali menggunakan narkoba setelah berhasil pulih) menjadi tinggi karena merasa tidak diterima untuk beraktivitas di masyarakat secara bebas. Penulis pernah mendengar langsung dari seorang mantan penyalahguna, bahwa dia mengalami relapse usai rehabilitasi hanya karena tidak diterima beribadah bersama masyarakat di lingkungan rumahnya.
Untuk itu diperlukan upaya anti-stigma yang beriringan dengan edukasi pencegahan dan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba karena menghapus stigma memiliki peran yang cukup penting untuk mempromosikan hidup sehat yang bebas dari adiksi.
Tulisan ini akan bersambung artikel bagian 2 berjudul ‘Gerakan #hapuskanstigma bagi Penyalahguna Narkoba’ pada bulan Februari 2022.
Penulis:
Adhika Pertiwi
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UGM 2021
Daftar Pustaka:
- Goffman, Erving. Stigma: Notes on the management of spoiled identity. s.l. : Touchstone, 1986.
- Muncan, B., Walters, Suzan M., Ezell, J., Ompad, D.C. “They look at us like junkies”: influences of drug use stigma on the healthcare engagement of people who inject drugs in New York City. 53, s.l. : Harm Reduction Journal, 2020, Vol. 17. https://doi.org/10.1186/s12954-020-00399-8
- Earnshaw, V.A. & Chaudoir, S.R. From conceptualizing to measuring HIV stigma: a review of HIV stigma mechanism measures. 6, s.l. : AIDS Behav, 2009, Vol. 13.
- Corrigan, Patrick W., et al. Developing a research agenda for reducing the stogma of addictions, Part II: Lessons from the mental health stigma literature. s.l. : The American Journal of Addiction, 2016, Vol. XX.